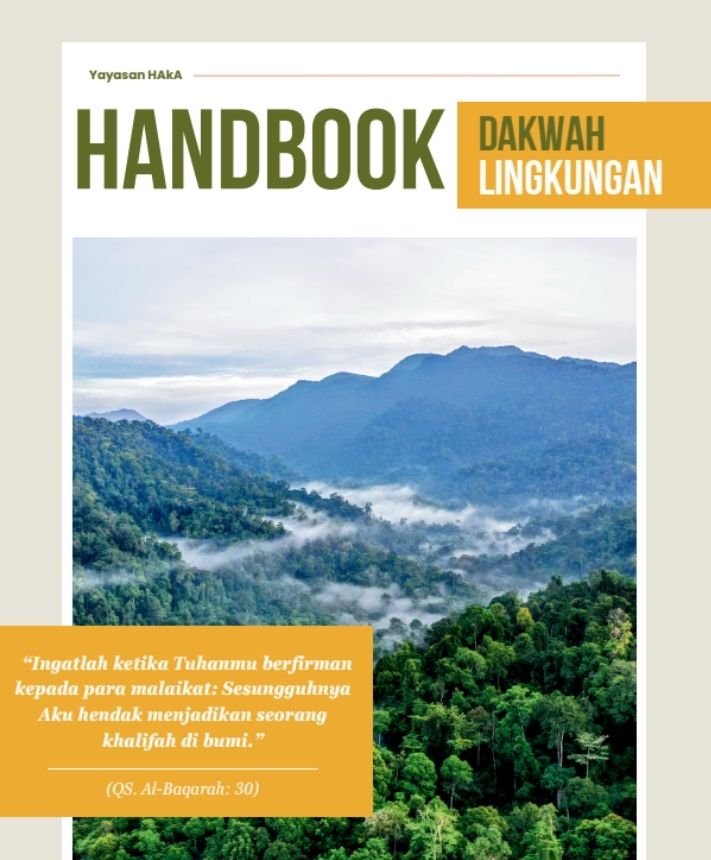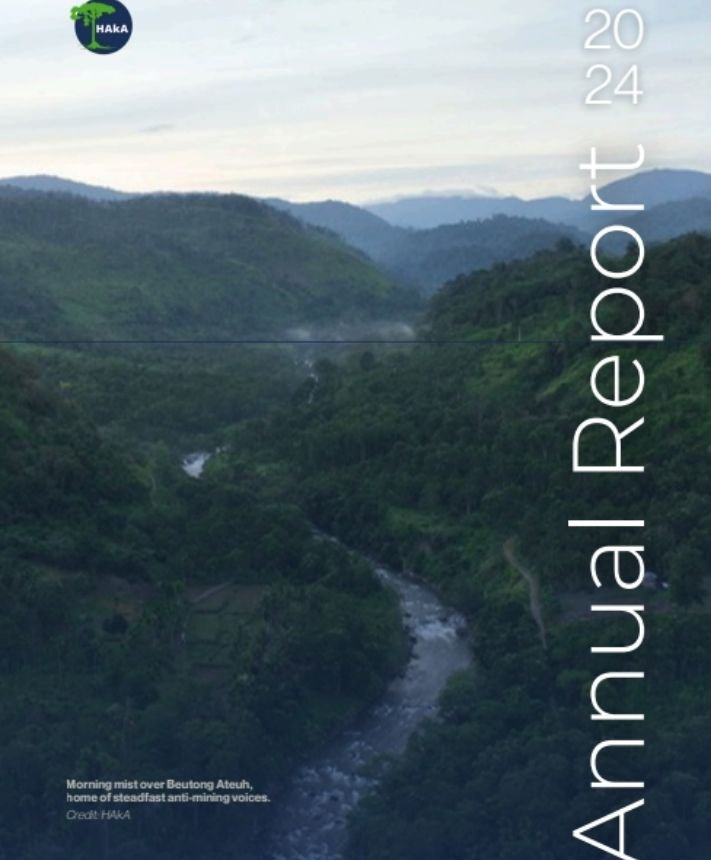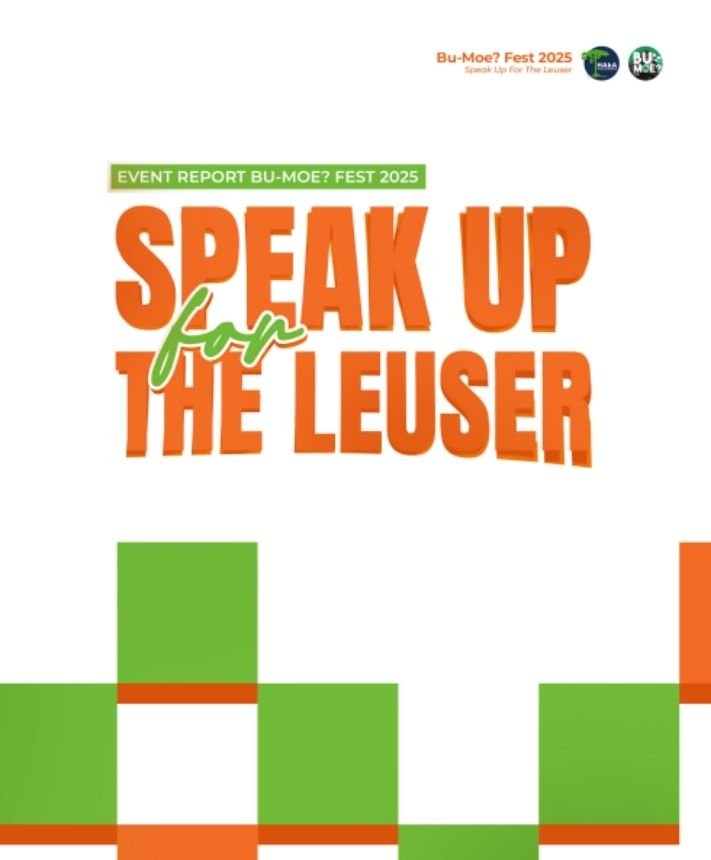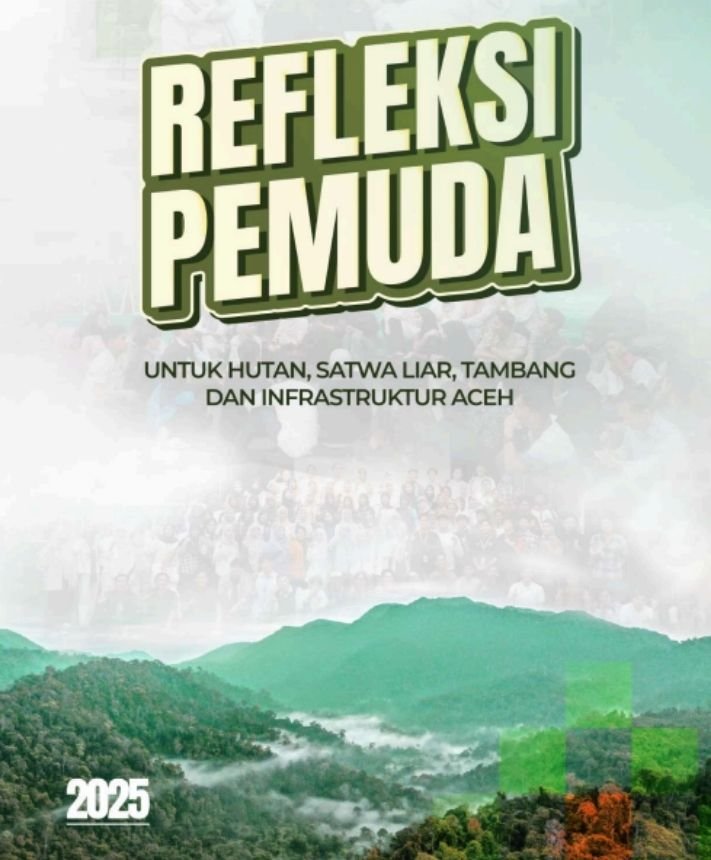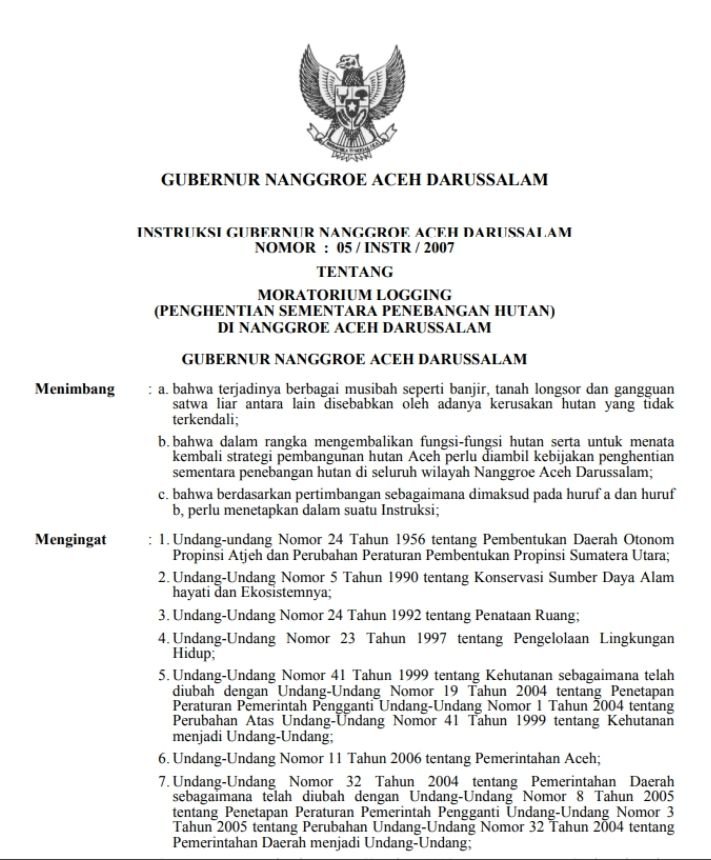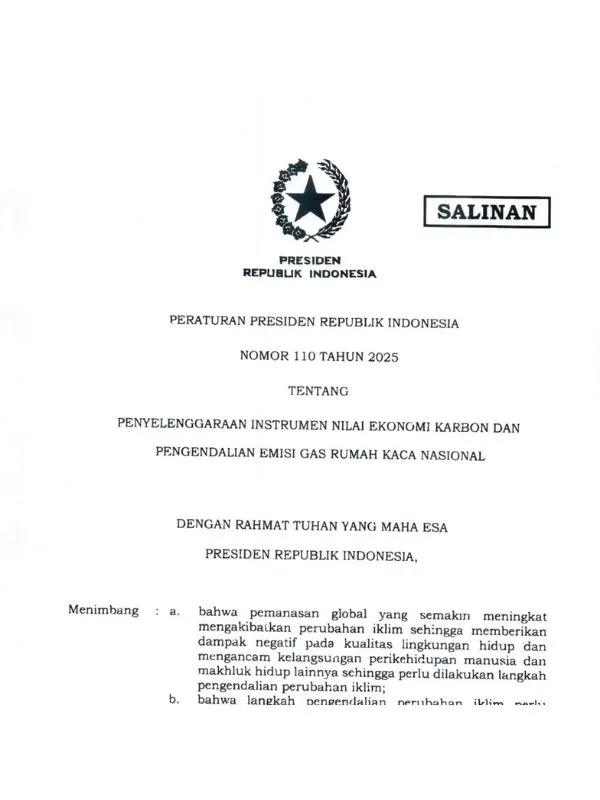- 19 Desember, 2025
- Komentar Dinonaktifkan pada Dari Linge: Perjalanan Bertahan Menuju Pulang
Dari Linge: Perjalanan Bertahan Menuju Pulang
Oleh: Hutari Nadhira, Rizkia Fardilla, dan Nurul Isnina
Perjalanan menuju Takengon kami awali bersama hujan yang turun tanpa jeda. Jalan basah, kabut tipis, dan suara air yang menghantam kaca mobil menjadi irama panjang yang mengiringi. Kami tiba di Takengon menjelang malam dan memilih bermalam, sebuah jeda singkat sebelum rangkaian hari yang jauh lebih panjang. Saat itu kami belum tahu, malam itu bukan sekadar istirahat, melainkan awal dari perjalanan yang akan menguras tenaga, pikiran, dan keberanian.
Keesokan harinya, kami melanjutkan perjalanan ke Linge untuk membantu persiapan Festival Nenggeri Linge II. Festival ini bukan sekadar acara budaya, melainkan ruang kolaborasi masyarakat untuk meneguhkan kembali jati diri Linge sebagai kawasan adat dan konservasi, merawat budaya, menjaga alam, dan menghidupkan nilai musarak dalam kehidupan sehari-hari. Hujan masih turun, dingin menusuk, tetapi semangat panitia tidak surut. Para ibu memastikan dapur tetap menyala, para bapak mendekor panggung dan mengangkat perlengkapan. Semua bergerak tanpa banyak bicara, seperti satu tubuh yang tahu perannya masing-masing. Di tengah cuaca yang tidak bersahabat, kebersamaan itu justru terasa hangat.
Pembukaan festival berlangsung meriah. Teman-teman dari Ekowisata hadir, bersama tamu dari kalangan akademisi Universitas Syiah Kuala, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, serta Jeffrey Michael Robbins, Konsultan Ekowisata dari Canopy. Salah satu momen paling membekas adalah kehadiran LK Ara, seniman legendaris Gayo, yang membacakan syairnya. Di bawah langit gelap dan hujan yang terus menderu, syair itu terdengar seperti doa, ia menenangkan, menguatkan, dan menyatukan. Malam ditutup dengan Didong Jalu. Kami basah dan lelah, tetapi bahagia karena semua berjalan sebagaimana mestinya.
Hari kedua festival, hujan belum juga berhenti. Kegelisahan mulai terasa, terutama karena agenda hari itu adalah arung jeram dan Tour de Linge, kegiatan yang mustahil dilakukan saat debit sungai terus naik. Rekan-rekan jurnalis mencoba mencari sinyal dan listrik hingga ke Pangmoed, sebuah kafe dan resto di jalan lintas Takengon–Blang Kejeren KM 56, namun hasilnya nihil. Mereka kembali membawa dokumentasi sungai yang kian liar dan sekantong bakso. Bakso itu kami makan keesokan paginya, terasa begitu “mewah”. Baru belakangan kami sadar, itulah makanan enak terakhir sebelum hari-hari berikutnya diisi Indomie yang dihemat, seiring logistik yang semakin menipis. Malam itu kami rapat. Agenda ditunda, penutupan disusun ulang, sambil menatap hujan yang seolah tak punya rencana berhenti.
Hari berikutnya seharusnya menjadi hari penutupan dan kepulangan. Namun pagi itu kabar buruk datang: jembatan penghubung Linge dan jalan menuju Takengon putus total. Rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh di dada. Kami terdiam beberapa detik, mencoba mencerna kenyataan bahwa kami benar-benar terisolasi. Kami tidak punya banyak waktu untuk larut. Ada puluhan orang yang harus dijaga, dan tanggung jawab yang lebih besar dari kepanikan pribadi. Rapat darurat dilakukan. Diputuskan empat orang akan diseberangkan lebih dulu, jika cuaca memungkinkan, untuk menyampaikan kabar bahwa kami terjebak dan membutuhkan bantuan. Kami menyepakati waktu tunggu: pukul 12 dan pukul 2, selama dua hari. Jika bantuan tak datang, kami harus keluar dengan cara kami sendiri. Belum selesai mencerna situasi, pengungsi dari desa tetangga mulai berdatangan. Tangisan mereka, cerita tentang keluarga yang terpisah, dan wajah-wajah penuh cemas menambah beban batin kami. Ironisnya, di tengah keterbatasan, Kampung Linge tetap menerima mereka. Saat itu, kami bahkan lupa bahwa kami sendiri sedang terisolasi, rasa kemanusiaan menyingkirkan rasa takut akan nasib sendiri.
Hari penyeberangan pertama tiba. Hujan sempat turun lagi, matahari tak kunjung muncul. Di situasi genting seperti ini, kepemimpinan menjadi nyata. Bang Abdul, Community Organizer kami, memimpin dengan tenang, mengecek aliran sungai, membaca arus, menimbang risiko, lalu menatap kami satu per satu, seolah memastikan kesiapan kami bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental.
Kondisi ekologis Linge saat itu benar-benar porak-poranda. Banyak pohon besar tumbang akibat longsor dan menutup jalan. Badan jalan hancur, sebagian amblas, menyisakan lubang-lubang dalam yang sulit dilewati. Tiang dan kabel listrik tumbang, melintang tak berdaya di tengah jalan. Jembatan penghubung yang selama ini menjadi nadi mobilitas warga putus total, membuat Linge terkurung dari dunia luar. Akses darat nyaris mustahil. Alam seperti menunjukkan kekuatannya dan kami berada tepat di tengahnya.
Dengan berat hati, kami memutuskan meninggalkan beberapa aset penting di Linge, mobil-mobil dinas dan perlengkapan yang tidak mungkin dibawa. Kami hanya membawa barang seperlunya. Tim awal diseberangkan, termasuk seorang jurnalis, agar apa yang terjadi di Linge bisa keluar. Kami melepas mereka dengan haru dan cemas. Saat mereka berhasil mencapai seberang, kami melambaikan tangan dari balik sungai yang lebar, lega karena pesan akan sampai, takut karena risiko yang baru saja mereka lewati.

Keberhasilan itu membawa kenyataan lain: logistik semakin menipis. Kami tidak bisa bertahan lebih lama. Keputusan sulit pun diambil, keesokan paginya, semua harus keluar desa dengan cara yang sama: menyeberangi sungai.
Sabtu, 29 November 2025, menjadi hari penyeberangan besar. Dua perahu karet yang semula disiapkan untuk festival berubah fungsi menjadi “jalan hidup” bagi 41 orang. Dengan dukungan beberapa profesional arung jeram yang kebetulan bersama tim kami, kondisi sungai dinilai memiliki arus deras dengan tingkat kesulitan grade 3+. Artinya, arus kuat, ombak sedang hingga besar yang tidak beraturan, pusaran air yang aktif, serta manuver yang sulit, ditambah beberapa terjunan miring yang berbahaya jika salah perhitungan.
Proses penyeberangan memakan waktu hampir tiga jam, tiga jam yang terasa seperti diuji berulang kali oleh arus, rasa takut, dan kecemasan. Tidak ada yang mengeluh tidak sanggup. Kami saling menunggu, saling memegang, memastikan tak ada yang tertinggal. Setelah berhasil menyeberang, perjalanan belum selesai. Kami masih harus berjalan kaki dan kembali berhadapan dengan longsoran lain yang tak kalah parah, menuntut kehati-hatian di setiap langkah.

Setelah berhasil menyeberang, kami menuju Desa Owaq dan bermalam. Kami diizinkan tidur di SMA Negeri 13 Takengon. Mandi di sungai menjadi pengalaman baru bagi beberapa orang namun bukan karena ingin, tapi karena keadaan menuntut begitu. Warga setempat membantu kami dengan cara yang paling tulus: menyisihkan sedikit dari beras mereka yang tersisa. Malam itu kami makan nasi hangat dengan Indomie yang dimodifikasi seadanya tetapi rasanya seperti jamuan besar, karena kami makan dengan rasa syukur.
Minggu, 30 November 2025, sebelum berangkat, kami selalu berkumpul dulu. Kami mengatur target harian, mengembalikan semangat, menata ulang keberanian. Target hari ini adalah Desa Uning. Kami sempat berfoto bersama, sebuah foto sederhana yang tulus tanpa tahu bahwa beberapa jam ke depan akan menjadi salah satu medan paling berat yang pernah kami lalui.

Kami melewati longsor ringan hingga longsor parah sepanjang kurang lebih 400 meter, dan butuh sekitar tiga jam untuk menembusnya. Tanah berubah menjadi lumpur tebal, hasil jalan yang longsor dan belum mengering. Tanah masih sangat basah, salah pijak sedikit saja, lumpur bisa mencapai dada orang dewasa yang mampu meneran siapapun. Sepanjang perjalanan, rasanya seperti mimpi buruk: jalan yang kemarin kami lalui dengan lancar kini runtuh total, hingga membuat kami lupa seperti apa bentuk utuhnya sebelumnya. Di sana, masyarakat setempat sedang bergotong royong membuat jalan darurat dari papan kayu. Mereka bekerja keras bukan untuk kami saja, tapi untuk membuka akses bagi semua orang. Melihat itu, ada perasaan kecil di hati: bahwa di tengah bencana, kemanusiaan justru sering muncul paling terang.
Longsor itu tidak menyurutkan semangat kami, tepi demi tepi lumpur yang licin itu tetap kami coba untuk lewati tapi kami hanyalah manusia biasa. Ganasnya medan membuat empat orang diantara kami jatuh pingsan. Tangisan menyertai. Saat itu, kami bukan lagi panitia, bukan lagi rombongan “kegiatan” namun kami menjadi warga biasa yang butuh ditolong. Dan warga-warga yang sedang bergotong royong itu menolong kami, menenangkan kami, membantu kami berdiri lagi. Perjalanan hari itu terasa sangat panjang. Energi terkuras, mental diuji habis-habisan. Di satu sisi kami harus menenangkan diri sendiri, di sisi lain kami sebagai panitia merasa bertanggung jawab menenangkan peserta yang sudah mulai memikirkan keluarga di rumah—apakah mereka aman, apakah mereka khawatir, apakah mereka tahu kami di mana.

Menjelang maghrib, keresahan mulai menekan: kami belum menemukan desa untuk singgah. Sesekali terlintas pikiran, “Apakah malam ini kami harus berhenti di jalan?” tetapi pikiran itu segera kami tepis. Kami terus berjalan sampai akhirnya tiba di Desa Uning. Kami ditolong oleh teman dari salah satu rombongan, dan keluarganya menerima kami meski mereka sendiri sedang susah. Mereka memperbolehkan kami tinggal, membantu kami mendapatkan air bersih meski air itu harus dicari melewati beberapa longsoran, dan memberi kami rasa aman di tengah situasi yang mencekam. Malam itu, kami tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya, karena setidaknya kami tidak sendiri.
Senin, 1 Desember 2025, kami melanjutkan perjalanan dengan target Desa Isaq. “Target hari ini Desa Isaq. Bagaimanapun medannya, walaupun seharian berjalan, yang penting sampai dengan sehat. Jangan terburu-buru.” Ucap Bang Abdul. Kalimat itu sederhana, tapi terdengar seperti pegangan hidup. Beberapa dari kami yang kurang sehat diantar dengan sepeda motor ke puskesmas. Sisanya kembali berjalan melewati longsoran, jalan patah, genangan, dan lumpur setinggi pinggang yang sudah menjadi “teman” paling setia. Pakaian sudah tidak berbentuk, tenaga seperti habis, dan frustrasi tiba-tiba memuncak: menangis dalam keputusasaan, bertanya dalam hati, “Berapa banyak lagi lumpur yang harus kami lewati?”

Lalu, suara motor trail lewat terdengar. Ada rasa akrab yang membuat kami spontan menghentikan tangis. Kami melihat barang-barang yang tidak terasa asing pada pengendaranya, dan tanpa yakin pun, kami memilih bertindak: berteriak, mencoba menghentikan motor itu. Dan ternyata benar. Bagaikan oase di tengah gurun, kami melihat tiga wajah familiar. Wajah teman kami yang diutus oleh kantor untuk menjemput. Kami sangat bersyukur. Di titik itu, beban seperti runtuh setengahnya. “Ternyata kantor tahu kalau kami sedang mengalami kesulitan ini,” begitu yang terus terucap di kepala kami, berulang-ulang, seperti memastikan bahwa ini nyata.
Kami diantar menggunakan truk ke posko yang dibuat swadaya oleh masyarakat. Kami diberi makan, diberi ruang untuk duduk, dan diberi kesempatan untuk bernapas. Strategi perjalanan disusun lagi: dibagi menjadi lima tim agar lebih efektif. Perjalanan berlanjut tidak jauh berbeda: ada bagian yang bisa dibantu kendaraan bak terbuka sampai titik terakhir yang dapat diakses, setelah itu kami berjalan lagi melewati longsor dan jalan yang terputus. Saat itu, kami sempat bertanya dalam hati, “Masih harus berjalan lagi? Mungkinkah kami sampai di Takengon hari ini?”

Tidak lama kemudian, tiga mobil 4x4 dan satu Innova Reborn datang. Awalnya kami kira warga sekitar yang ingin melintas. Tapi seseorang yang sangat kami kenal pun turun, seorang rekan kerja yang selalu mendampingi kami ketika di lapangan. Tangis kembali pecah. Kami merasa semakin dekat dengan pulang. Di hari itu, kami merasa tidak ada yang sia-sia dari pengorbanan kami. Kami merasa berharga—bukan karena kami hebat, tetapi karena kami bertahan bersama. Kami tidak menyangka, hari itu akan menjadi hari terakhir perjalanan, dan kami akan kembali ke Takengon. Rasanya seperti mimpi yang nyaris tak nyata.
Kami tiba di Takengon dan disambut oleh Tim HAkA yang sudah menunggu. Haru, lega, dan bingung bercampur jadi satu. Awalnya kami kira hanya kami yang mengalami hal seperti ini, lalu kami sadar: bencana ini jauh lebih besar, dampaknya meluas, dan ribuan jiwa turut terdampak.
Perjalanan ini, pada akhirnya, bukan sekadar cerita tentang hujan, longsor, sungai deras, jalan putus atau perubahan alam yang kami saksikan berbalik 180 derajat di depan mata. Ini adalah cerita tentang manusia yang terus bergerak menuju selamat, tentang tubuh yang dipaksa berjalan saat tenaga hampir habis, dan tentang mental yang dipaksa kuat saat hati ingin runtuh. Yang menyelamatkan kami adalah satu kesatuan: kepemimpinan, daya juang, dan kekompakan. Tidak ada yang mengeluh tidak sanggup, meski medan yang kami tempuh sangat sulit. Kami saling menjaga: dengan tangan, dengan kata-kata, dengan kesediaan untuk menunggu, dan dengan keberanian untuk tidak meninggalkan siapa pun.
Dan mungkin, di balik semua itu, ada alasan paling manusiawi yang membuat kami terus berjalan: kami ingin selamat, ingin segera berkumpul lagi dengan keluarga di rumah, dan ingin memastikan bahwa setelah semua yang terjadi, kami masih bisa memeluk orang-orang yang kami cintai, dengan rasa syukur yang tidak akan sama lagi seperti sebelum perjalanan ini dimulai.